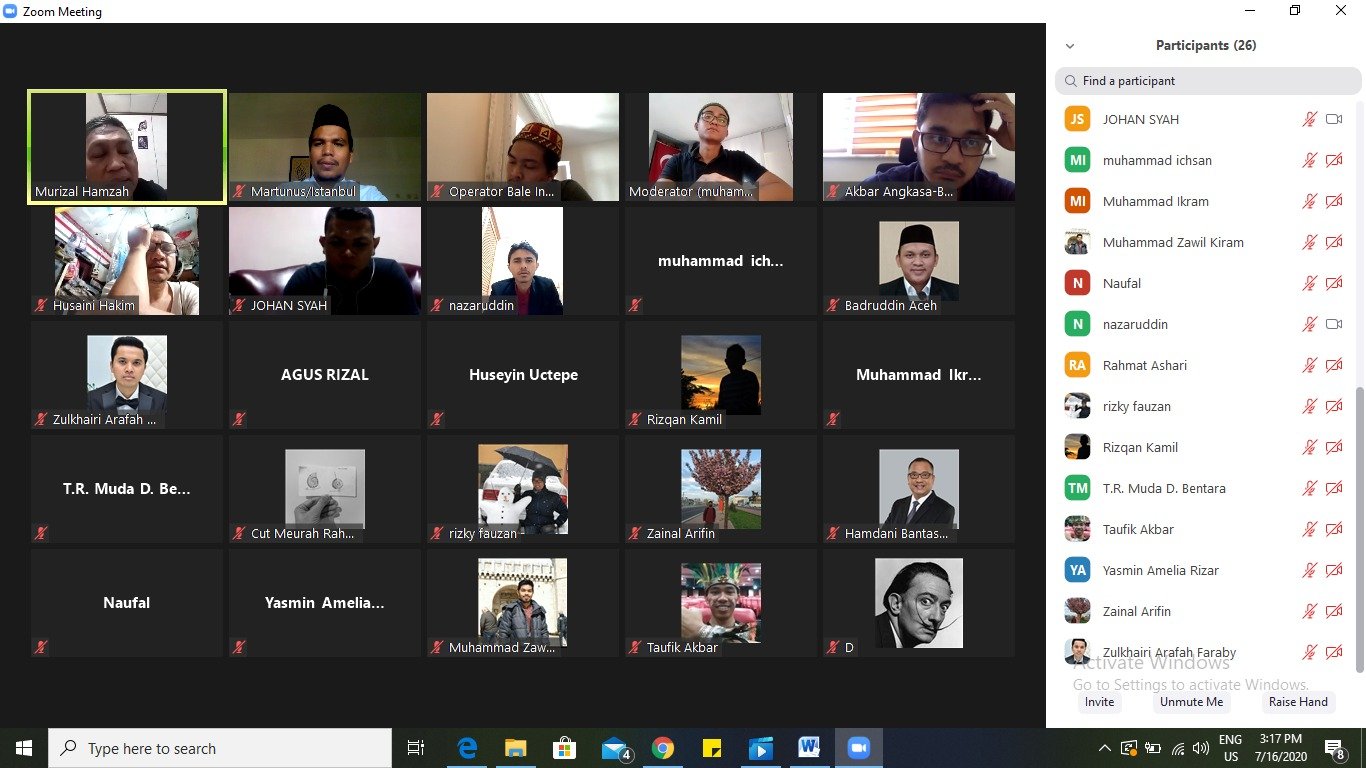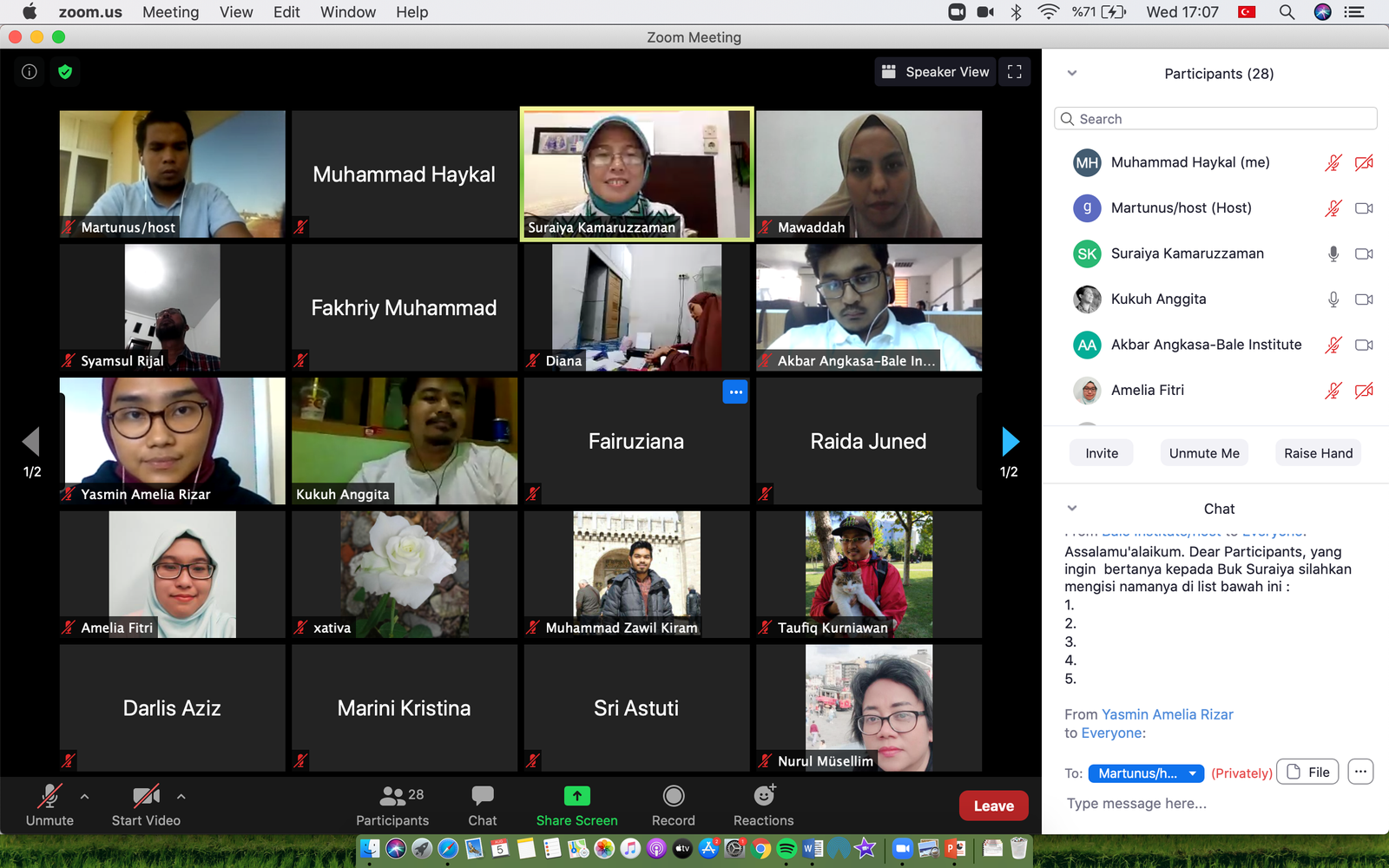Minggu, 19 Juli 2020 – Bale Institute bekerja sama dengan PPI Istanbul menggelar diskusi virtual Çay Peradaban yang dihadiri oleh Adhe Nuansa Wibisono atau yang akrab disapa dengan Mas Wibi, kandidat doktor bidang studi terorisme Keamanan Internasional di Akademi Polisi Ankara dan pendiri Cakramandala Institute. Dalam presentasinya, mas Wibi mengulas isu Ayasofya dari aspek yang menyuluruh seperti; isu sejarah, politik dalam dan luar negeri dan kaitannya dengan isu keislaman di dunia.
Dilihat dari sejarahnya, Konstantinopel direbut oleh Kesultanan Usmani dengan cara perang. Dengan demikian, secara otomatis beberapa unit atau properti dalam kota tersebut jatuh dalam status ghanimah atas peperangan tersebut. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasanya Sultan Muhammad al-Fatih membeli Ayasofya tergolong kurang tepat karena bercanggah dengan prinsip tersebut. Setelah penaklukkannya, maka Ayasofya dijadikan Mesjid oleh Sultan Fatih dalam titah surat waqaf yang disimpan hingga saat ini. Perubahan status juga mengakibatkan perubahan fungsi yang mana sebelumnya merupakan sebuah katedral, setelah menjadi masjid, Ayasofya disamping menjadi tempat ibadah juga dijadikan sebagai pusat kegiatan sosio-religius dan pendidikan.
Pada tahun 1934, tepat sepuluh tahun setelah terbentuknya Republik Turki, atas permintaan pemerintah Amerika pada waktu tersebut, Ayasofya diubah menjadi museum. Hal ini berlangsung hingga tahun 2020, dengan keluarnyakeputusan majelis dan persetujuan/dekrit Presiden Erdogan atas perubahan dari museum menjadi masjid.
Sepanjang sejarah politik internal Turki post-republik, Ayasofya dijadikan sebagai simbol perjuangan golongan konservatif. Hal tersebut dibuktikan dengan ucapan Necip Fazil Kisakurek, Necmettin Erbakan dll yang menjanjikan bahwa kuasa politik konservatif akan memuncak sehingga mampu merubah status Ayasofya.
Pengubahan status Ayasofya oleh Erdogan disamping menyimbolkan kemenangan kaum konservatif juga menjadi bahan pembicaraan politik internal. Khususnya para oposisi, melihat dari kacamata untung rugi-politik, menafsirkan bahwa Erdogan ingin menyegarkan reputasinya untuk pemilu 2023 mendatang. Mereka menuduh Erdogan menggunakan instrumen agama untuk kepentingan politik, yang mana itu adalah hal yang tidak sepatutnya dilakukan.
Dunia Barat seperti Yunani, Vatikan, dan juga Amerika menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan keputusan Turki. Namun, Erdogan menangkis argumen tersebut dengan menegaskan bahwa keputusan Ayasofya adalah isu dalam negeri Turki. Ketegasan Erdogan menyirati sebuah kepribadian teguh dalam berdaulat, dan keinginan untuk memposisikan Turki setara dengan pemain politik dunia Internasional seperti Rusia dan Amerika. Bukan hanya itu, Erdogan juga memberikan pesan bahwa keputusan ini merupakan langkah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsha. Secara tidak langsung Erdogan juga ingin memberikan semangat kepada Dunia Islam untuk memperteguhkan kembali sikap percaya diri dan terlepas dari inferiority-complex yang diakibatkan oleh kolonialisme.
Setelah menjelaskan presentasinya secara general, mas Wibi menanggapi beberapa pertanyaan dari audiens diskusi virtual. Isu yang dibahas meliputi; teknik berkunjung ke Ayasofya setelah konversi menjadi masjid dan isu sistem millet yang diadopsi oleh Usmani ketika membentuk relasi dengan warga-negara yang non-muslim. Terkait kunjungan, pihak direktorat agama Turki sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sistem pencahayaan yang menutupi ikonik Kristen ketika dilaksanakan ibadah. Adapun isu sistem millet, merupakan suatu benih pembentukan sistem citizenship modern. Dalam konsep millet, walaupun berbeda agama, maka hak untuk melaksanakan ibadah dan kehidupan sosial dikenal oleh pemerintah. Dengan demikian, kaum ortodoks, yahudi dan Islam memiliki institusi agama masing-masing yang bersifat independen dan patuh pada otoritas Sultan. Oleh karena itu, Usmani dapat memberikan solusi dengan pendekatan pluralis kepada seluruh anggota minoritas. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai citizenship/kewarganegaraan dalam konsep negara-bangsa.
Setelah diskusi berlalu sekitar satu setengah jam, diskusi virtual pun diakhiri dengan kata hamdalah dan do’a kafaratul majlis. Ucapan terima kasih dilanturkan kepada penanggung jawab acara.