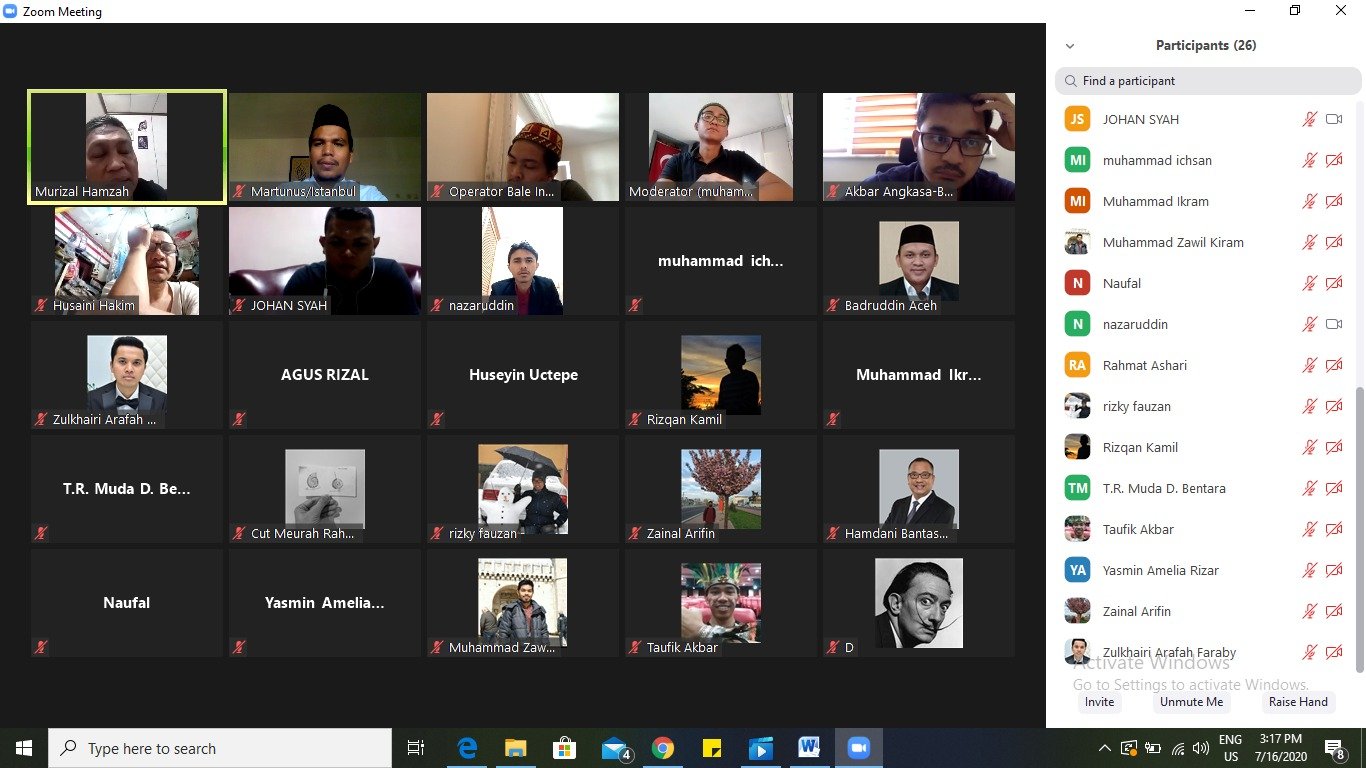Notulen: Mawaddah Idris & Taufiq Kurniawan
Rabu – 5 Agustus 2020, Bale Institute mengadakan acara Diskusi Virtual ke-5 dengan narasumber Suraiya Kamaruzzaman, M.T. salah seorang aktivis perempuan di Aceh. Diskusi Virtual kali ini bertajuk “Peran dan Pemberdayaan Perempuan Aceh Pasca Konflik.”
Sebagai tonggak peradaban, perempuan mempunyai kedudukan mulia di dalam kehidupan. Di Aceh perempuan mempunyai peran penting dari masa ke masa. Jika mengkaji aspek historis, wanita Aceh memegang peran strategis dalam bidang politik, pemerintahan, pertahanan dan juga kepemimpinan. Keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek di Aceh ini, bisa ditelusuri sejak abad ke 14. Dalam bidang kepemimpinan Aceh juga pernah dipimpin oleh empat orang Sultanah yang berlangsung 59 tahun lamanya. Dalam bidang kemiliteran, nama Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia juga telah membawa Aceh pada puncak kejayaan pada masanya.
Dengan latar belakang sejarah dan kegemilangan kaum perempuan dalam peradaban Aceh, tidak mengherankan bila hingga saat ini semangat para pejuang mengalir dalam darah wanita Aceh. Konflik yang berkepanjangan juga menjadi faktor yang membentuk karakteristik perempuan Aceh begitu kuat. Salah satu perempuan Aceh yang telah banyak berkontribusi untuk Aceh khususnya setelah masa konflik adalah Suraiya Kamaruzzaman yang melalui upayanya untuk membela hak-hak perempuan Aceh, ia acap kali mendapatkan penghargaan dari dalam dan luar negeri.
Dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Bale Institute, tema yang dibahas adalah peran dan pemberdayaan perempuan Aceh pasca konflik. Di moderatori oleh Mawaddah yang merupakan alumni Selcuk University jurusan Jurnalistik, diskusi berlangsung dengan khidmat dan interaktif. Peserta yang menghadiri diskusi datang dari berbagai kalangan, terdiri dari mahasiswa di berbagai jenjang strata pendidikan yang sedang menempuh studi di Luar Negeri,antara lain Turki dan Amerika. Kemudian juga turut hadir Prof Syamsul Rizal yang merupakan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerja sama UIN Ar-Raniry Aceh dan beberapa partisipan yang berasal dari luar Aceh.
Diawali dengan pemutaran Himne Aceh, lalu dilanjutkan dengan pemaparan diskusi oleh pemateri. Suraiya membuka presentasi dengan memaparkan hasil kerjanya bersama teman aktivis perempuan lainnya yang ada di Aceh. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa aktivis perempuan di Aceh banyak peran namun sedikit terdokumentasikan, sudah banyak berbuat namun sedikit pengakuan dan banyak keberhasilan namun hanya sedikit sekali yang terpublikasikan. Upayanya dalam membela kaum perempuan di Aceh telah dimulai sejak konflik berkepanjangan antara RI dan GAM. Meski telah memasuki tahun ke 15 damai Aceh pasca Mou Helsinki, isu perempuan tidak terdapat dalam perjanjian damai tersebut. Hal ini tidak membuat sosok perempuan tangguh ini berputus asa. Karenanya hal ini juga yang kemudian menginisiasi terbentuknya LINA (Liga Inong Aceh) yang di turut dipelopori oleh Shadia Marhaban yang merupakan aktivis dan Internasional mediator di Aceh.
Perempuan Aceh pasca konflik, mengalami permasalahan yang kompleks. Isu kekerasan dan pelecehan seksual, partisipasi perempuan dalam ruang politik serta implementasi syariat Islam yang kerap kali mengesampingkan perempuan menjadi bahasan pokok dalam diskusi ini. Contoh dari implementasi syariat Islam yaitu ketika seorang wanita yang ketahuan melakukan khalwat mendapatkan tindakan pelecehan oleh para penggerebek di Aceh Timur, si wanita tetap dihukum cambuk sedangkan pelaku pelecehan tidak mendapat hukuman apapun. Selain itu juga ada kasus perempuan Down Syndrome yang menjadi korban pelecehan, hasilnya bukan malah diberikan perlidungan, malah diberi hukuman dengan cara pengusiran dari tempat kediamannya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan asas syariat Islam yang mana melindugi hak orang yang terzalimi.
Maka kesimpulannya; ada banyak tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan di Aceh, diantaranya: Komitmen Pemerintah masih lemah terhadap perlindungan perempuan, kebijakan tentang penguatan peran perempuan dalam pembangunan perdamaian belum menjadi prioritas, perempuan belum terbebas dari kekerasan, partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal, legislasi yang diprioritaskan tidak berorientasi pada kesejahteraan dan perdamaian dan cenderung diskriminatif dan ketidakpekaan pemerintah terhadap pemenuhan hak korban diskriminatif.
Dalam meningkatkan peran perempuan Aceh ada 5 langkah yang bisa dilalui. Pertama, Capacity Building, yaitu sebuah proses yang dapat meningkatkan kemampuan para wanita Aceh. Kedua, Advokasi kebijakan/anggaran; untuk melindungi hak-hak perempuan dari peraturan-peraturan yang mendiskriminasikan kaum hawa, seperti larangan duduk ‘ngangkang’ dimotor yang sempat menjadi polemik di Aceh Utara, kewajiban memakai rok di Aceh Barat, dan lain-lain. Ketiga, pembangunan RPPA (Rumah Perempuan Politik Aceh) pada tahun 2010, yang mana tempat ini difungsikan sebagai tempat para kaum perempuan belajar berpolitik. Keempat, kampanye perdamaian dan anti kekerasan, hal ini dilakukan baik di dalam maupun luar negeri. Kelima, Duek Pakat Inoeng Aceh, pada tanggal 28-30 Maret 2011 pernah dilaksanakan Kongres Perempuan Aceh ke III yang bertema ”Berjuang Untuk didengar”. Pada kongres ini juga dibahas mengenai diskriminasi terhadap perempuan pada penerapan syariat Islam, sebagai contoh perberlakuan hukuman cambuk kepada perempuan korban pelecehan, gugurnya suatu perkara ketika lelaki pelaku pelecehan ikut bersumpah di pengadilan, dan lain-lain.
Ada beberapa strategi dalam melindungi hak perempuan. Diantarannya, memperluas jaringan kerjasama baik tingkat lokal, nasional bahkan internasional; membangun kader muda melalui sekolah-sekolah pengkaderan perempuan; berkerjasama dengan pemerintah terutama dengan P2tp2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak) serta dinas PPA; bersosialisasi dan beradvokasi; mendorong partisipasi politik perempuan; menguatkan media mainstreamdan sosial media; serta memperkuat hak kespro, ekonomi dan pendidikan perempuan. Agar strategi ini berhasil perlu didukung oleh nilai pergerakan (ideologi), visi dan misi kebenaran; penguasaan ilmu pengetahuan dan skil; jiwa kreatif; serta do’a. Dalam pengembangan ini aktivis pembela hak perempuan mendapatkan beberapa hambatan, diantaranya: fundamentalisme, radikalisme dan kurangnya solidaritas.
Setelah sesi penyampaian materi oleh narasumber berakhir, dimulai dengan sesi interaktif, tanya jawab dan respon dari para peserta. Pertanyaan pembuka diawali oleh Yasmin Amelia yang merupakan Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional di Istanbul Medeniyet University, Istanbul. Ia bertanya mengenai apa yang menyebabkan partisipasi politik perempuan masih kecil di Aceh. Hal ini direspon dengan penjabaran yang sangat detail oleh narasumber. Hal mendasar yang melatarbelakangi minimnya partisipasi perempuan dalam politik adalah sistem patriarki yang berkembang di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pola pikir dan sistem sosial yang menempatkan lelaki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam sosial politik, membuat perempuan tidak menaruh perhatian yang signifikan terhadap isu sosial dan politik. Dengan budaya yang berkembang di Aceh saat ini, perempuan lebih identik dengan urusan domestik. Padahal bila tidak ada ruang bagi perempuan dalam ranah politik, hal ini akan mengakibatkan kebijakan yang diambil tidak memihak kepada perempuan karena lelaki tidak memiliki pengalaman yang sama dengan perempuan sehingga mereka tidak paham kondisi biologis hingga psikologis yang dialami oleh perempuan. Pemateri mencontohkan aturan tentang larangan duduk mengangkang yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, hal ini hanya dilihat dari satu sisi saja padahal banyak aspek lain yang justru bisa di kaji kembali. Salah satunya, penggunaan sepeda motor yang umumnya digunakan oleh kelas sosial menengah kebawah yang mana akan sangat menyusahkan bila mereka menggendong anak sambil dibonceng dan ini juga bisa membahayakan keselamatan.
Menurut padangan Suraiya, syariat Islam harusnya menjadi ruh kebangkitan kejayaan Islam di Aceh seperti masa lampau. Penegakan syariat Islam hari ini dinilai belum memenuhi esensi dan kaidah sebagaimana yang telah diatur sedemikian baik dalam agama. Jauh sebelum isu feminisme berkembang di Barat. Islam telah mengatur segala tata cara dalam kehidupan termasuk bagaimana cara memperlakukan perempuan. Aturan yang berlaku di Aceh masih mendiskriminasikan perempuan berdasarkan gender. Banyak ruang yang bisa diisi oleh perempuan dalam masyarakat namun mendapat tantangan dari berbagai elemen masyarakat karena belum bijak dalam memahami dan mengimplementasikan syariat Islam.
Pertanyaan kedua dari Ibu Raida Juned. Bagaimana pendapat ibu Surayya mengenai hadist tentang sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang berada di rumah? ibu Suraiya tidak menjawab tentang penjelesan hadis tersebut, tetapi beliau hanya menyampaikan tentang kehidupan yang terjadi pada masyarakat, sebagai contoh pada hari ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selain suami, para istri juga harus wajib berkerja. Sampai disini tidak ada kendala, tetapi mulai muncul kendala ketika tugas mencari nafkah dilakukan oleh kedua pasangan, sedangkan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan lain-lain tetap jadi tangung jawab sang istri. Disini perempuan menjadi terbebani. Jadi alangkah baiknya bila suami juga ikut membantu istri dalam urusan pekerjaan rumah.
Sebelum diskusi di tutup, Prof Syamsul Rizal juga memberi tanggapannya mengenai isu perempuan yang saat ini sedang berkembang di Aceh. Menurutnya hal ini menjadi persoalan bersama yang harus dicari solusi. Bahwa sejatinya peran dan kedudukan perempuan sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan kategori tertentu dalam berbagai konteks yaitu; individual dan sosial. Ia memandang secara konsep individual, perempuan Aceh tidak memiliki persoalan seperti kebebasan beribadah, namun di dalam konteks sosial, ia melihat terdapat beberapa kejanggalan yang mesti dituntaskan. Namun demikian, dibandingkan dengan negara dan daerah lain, aspek keseteraan gender yang telah diraih di Aceh sudah sangat lumayan.
Pertanyaan terakhir sekaligus merangkum diskusi disampaikan oleh M. Akbar Angkasa mahasiswa pasca sarjana jurusan Sosiologi Ibn Haldun University, yang menanyakan tanggapan Suraiya mengenai pemberitaan negatif tentang Aceh di media internasional. Pembicara menyatakan bahwa framing yang tidak tepat dari media ini berasal dari proses pengimplementasian syariat Islam yang masih belum baik di Aceh sehingga menjadi celah bagi media asing untuk mencari kesalahan dalam penerapan aturan Islam. Harusnya dengan penegakkan syariat Islam yang benar, justru bisa menjadi contoh bagi dunia luar bahwa Islam adalah agama yang rahmatalil ‘alamin papar Suraiyya.
Pada akhir diskusi, moderator merangkum beberapa poin antaranya telah banyak upaya yang dilakukan oleh aktivis perempuan Aceh dalam melindungi dan membela hak perempuan di Aceh. Program ini terbagi dalam capacity building, advokasi kebijakan/anggaran, mendorong partisipasi perempuan, kampanye perdamaian, hingga peran sebagai peace builder. Rangkuman program ini terus dijalankan sembari memberikan edukasi dan pembinaan hingga pemberdayaan terhadap perempuan di berbagai daerah. Lalu kemudian diskusi ditutup dengan harapan agar persoalan perempuan di Aceh ini dapat menjadi permasalahan bersama yang dapat merangkul semua golongan dan gender. Lelaki juga sangat berperan dalam mendampingi dan mendukung